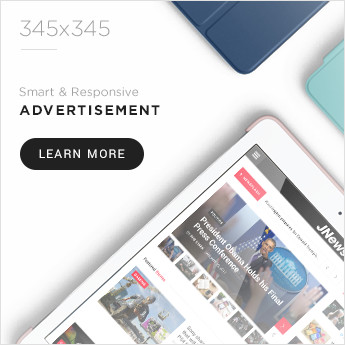Oleh : Syafaat *
Rahim itu sunyi, tak tampak dalam pidato dan perayaan, namun di sanalah masa depan disusui dengan kesabaran, doa, dan pengorbanan. Maka ketika Hari Ibu diperingati, yang sesungguhnya kita hormati bukan sekadar sosok ibu, melainkan rahim peradaban itu sendiri, tempat kehidupan dimulai, nilai ditanamkan, dan arah bangsa diarahkan. Logo Hari Ibu dengan bunga melatinya hadir sebagai isyarat lirih: bahwa kekuatan sejati tidak selalu bersuara keras, dan masa depan tidak dilahirkan dari ambisi, melainkan dari rahim kesucian, ketulusan, dan kasih yang setia merawat waktu.
Logo Hari Ibu tahun ini menghadirkan bunga melati, kecil, putih, nyaris tak bersuara. Ia seperti doa yang dilafalkan dalam rahim sunyi, tak diperdengarkan, namun sampai ke hadirat-Nya. Dalam kemerdekaan melaksanakan dharma, melati tidak memekik seperti mawar yang menuntut pandang, tidak pula mencolok seperti anggrek yang ingin dipuji. Ia memilih jalan rendah, dan justru dari kerendahan itulah kesucian bersemi. Melati tidak meminta disanjung; ia mengharumkan ruang dengan setia. Begitulah ibu: sering tak disebut dalam pidato, jarang diangkat dalam perayaan, namun dari rahim dan kesabarannya arah hidup dituntun. Ia memerdekakan dengan kasih, mendidik dengan diam, dan menguatkan dunia tanpa suara. Tanpanya, hidup kehilangan poros, sebab doa-doa paling sampai sering lahir dari yang paling sunyi.
Melati tumbuh dari akar budaya yang panjang, berjejak pada tanah yang sabar menerima musim. Ia tidak lahir dari tanah yang tergesa-gesa, melainkan dari bumi yang diolah dengan ketekunan. Di sanalah ia belajar bertahan: dari hujan yang tak selalu ramah, dari panas yang menguji keteguhan. Melati mengajarkan bahwa kekuatan perempuan Indonesia bukanlah kekuasaan yang menghentak meja, bukan suara yang meninggi untuk menang. Kekuatan itu adalah ketabahan yang setia merawat waktu, menunggu benih menjadi pohon, menunggu luka menjadi pelajaran, menunggu bangsa dewasa dalam nurani.
Warna emas dan merah putih yang mengiringinya bukan sekadar perhiasan visual. Emas adalah ingatan tentang kejayaan yang seharusnya diraih dengan keluhuran budi, bukan dengan tipu daya dan lupa diri. Ia mengingatkan bahwa kemuliaan tidak lahir dari kerakusan, melainkan dari kejujuran yang dijaga meski sunyi. Emas adalah cahaya yang seharusnya menerangi, bukan menyilaukan. Sementara merah putih bukan sekadar warna, melainkan darah dan doa yang menjelma tanda. Merah adalah keberanian yang berdetak di nadi bangsa, denyut yang lahir dari luka dan pengorbanan. Putih adalah niat yang dijaga tetap bening, agar perjuangan tidak tercemar oleh dendam dan kepentingan sempit. Di dalamnya tersimpan kerja yang tak selalu tampak, keringat yang tak selalu mendapat nama, serta pengorbanan yang sering luput dari catatan sejarah. Semuanya berpaut pada satu keyakinan sunyi: bangsa ini tidak lahir dari kebetulan, melainkan dari rahim perjuangan yang panjang.
Dan rahim, selalu milik perempuan. Ia adalah tempat ternyaman dan teraman bagi tumbuhnya kehidupan, ruang sunyi tempat harapan dirawat dalam gelap. Dari rahim itulah kehidupan dimulai, dari sakit yang diterima dengan ikhlas, dari doa yang dipanjatkan tanpa pamrih, dari kesabaran yang tak menuntut balasan. Namun dari mulut rahim yang sama, sering pula lahir kecemasan dan persoalan: tangisan, risiko, bahkan kehilangan. Di sanalah perempuan menanggung paradoks kehidupan, menjadi pintu masuk bagi kehidupan sekaligus menanggung segala kemungkinan deritanya. Tetapi justru dari keberanian menanggung itulah, peradaban menemukan maknanya yang paling dalam.
Maka logo itu sesungguhnya bukan sekadar gambar. Ia adalah pengingat. Bahwa di balik kemajuan yang ingin kita capai, ada nilai-nilai yang harus tetap dijaga. Bahwa sebelum bangsa ini bermimpi menjadi emas, ia harus terlebih dahulu setia pada kesucian, ketulusan, dan kesabaran, nilai-nilai yang sejak awal dirawat oleh perempuan, setia, dalam sunyi. Namun, simbol hanya akan menjadi poster jika tidak diterjemahkan dalam laku. Kepemimpinan perempuan yang digaungkan tidak cukup berhenti pada kursi jabatan atau angka keterwakilan. Kepemimpinan perempuan sejati adalah kepemimpinan yang memanusiakan. Ia tahu kapan harus tegas, dan kapan harus menunggu. Ia tahu bahwa keberlanjutan bukan sekadar pembangunan yang ramah lingkungan, tetapi juga ramah batin. Dunia yang rusak seringkali bukan karena kurang teknologi, melainkan karena kehilangan kasih.
Sejarah Hari Ibu di Indonesia lahir dari Kongres Perempuan 1928. Saat itu, perempuan belum berbicara tentang bonus demografi atau revolusi digital. Mereka berbicara tentang martabat, pendidikan, dan nasib anak-anak perempuan yang ingin keluar dari gelap. Di ruang sederhana Yogyakarta itu, para perempuan menanam benih peradaban. Mereka tidak tahu bahwa puluhan tahun kemudian, benih itu akan kita sebut sebagai fondasi Indonesia Emas. Tetapi mereka tahu satu hal: bangsa tidak akan pernah besar jika setengah dari jiwanya dibiarkan kecil.
Dalam ajaran agama, ibu menempati posisi yang nyaris tak tertandingi. Nabi menyebut “ibumu” tiga kali sebelum “ayahmu”, seakan ingin menegaskan bahwa cinta paling sunyi justru yang paling berat bebannya. Surga diletakkan di bawah telapak kaki ibu, bukan karena ibu ingin disembah, tetapi karena dari ketaatan kepada ibu, manusia belajar merendahkan ego. Doa ibu melesat tanpa sekat, sebab ia lahir dari luka yang tidak pernah benar-benar sembuh: luka mengandung, melahirkan, menyusui, dan melepaskan.
Ibu adalah madrasah pertama. Dari suaranya, anak belajar mengenal Tuhan. Dari pelukannya, anak mengenal dunia. Maka ketika kita bicara tentang Indonesia Emas 2045, pertanyaan paling jujur bukanlah seberapa cepat teknologi kita, melainkan seberapa sehat rahim sosial kita. Apakah perempuan diberi ruang aman untuk tumbuh? Apakah ibu diberi waktu untuk mendidik tanpa dihimpit ketakutan ekonomi? Apakah kepemimpinan perempuan dimaknai sebagai kekuatan etik, bukan sekadar kosmetik demokrasi?
Gerakan perempuan yang progresif, sebagaimana dibayangkan dalam desain Hari Ibu 2025, seharusnya melangkah ke depan tanpa kehilangan jejaknya di tanah asal. Ia boleh berlari bersama zaman, menyentuh teknologi, menembus batas-batas lama, tetapi akarnya mesti tetap menghunjam ke bumi nilai. Sebab pohon yang tumbuh tinggi tanpa akar yang kuat hanya menunggu waktu untuk tumbang. Kemajuan yang tercerabut dari kearifan hanya akan melahirkan kelelahan baru, bukan peradaban.
Perempuan Indonesia tidak sedang menuntut keistimewaan, apalagi pengunggulan yang meminggirkan yang lain. Yang diminta hanyalah kehadiran yang utuh dan adil. Kehadiran sebagai pemikir yang suaranya didengar, sebagai pengasuh yang jerih payahnya dihargai, sebagai pemimpin yang kebijaksanaannya dipercaya, dan sebagai penjaga nurani bangsa yang kepekaannya tidak diremehkan. Dalam diri perempuan, akal dan kasih tidak saling meniadakan. Justru di sanalah keduanya berdamai, lalu melahirkan keputusan yang manusiawi.
Hari Ibu bukanlah perayaan sentimentil yang cukup ditebus dengan bunga dan unggahan media sosial. Ia bukan sekadar hari untuk mengucapkan terima kasih lalu kembali lupa esok pagi. Hari Ibu adalah saat berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan bertanya dengan jujur kepada nurani kolektif kita: apakah bangsa ini telah cukup adil kepada perempuan? Apakah kebijakan yang lahir dari meja-meja rapat sungguh ramah kepada ibu, atau justru menambah beban yang harus dipikul dalam diam? Apakah masa depan yang kita bangun hari ini layak diwariskan kepada anak-anak yang baru belajar mengeja kehidupan dari kata paling awal yang mereka kenal: “ibu”?
Jika Indonesia sungguh ingin menjadi emas, maka kilau itu tidak boleh hanya tampak di statistik dan pidato. Ia harus memancar dari nilai yang hidup, dari keadilan yang dirasakan, dari kasih yang diwujudkan dalam kebijakan dan laku sehari-hari. Dan nilai itu, sejak awal sejarah, dijaga dengan setia oleh perempuan. Seperti melati, ia tidak berisik, tidak menuntut sorak. Tetapi tanpanya, rumah kehilangan aroma, dan bangsa kehilangan arah pulang.
* Syafaat (ASN / Ketua Lentera Sastra Banyuwangi)